Seratusan tahun lalu, hiduplah seorang fisikawan berkebangsaan Inggris, William Thomson Kelvin namanya. Dunia lebih mengenalnya dengan panggilan Lord Kelvin. Beliau menggunakan nama belakangnya sebagai satuan temperatur yang ia temukan. Satuan Kelvin pada akhirnya ditetapkan sebagai standar satuan internasional untuk mengukur suhu pada tahun 1950. Kita ingat setidaknya ada 4 macam jenis termometer dengan satuannya masing-masing. Ada Celcius, Reamur, Fahrenheit, dan yang terakhir Kelvin.
Kenapa termometer harus bermacam-macam? Kenapa tidak satu jenis saja? Ternyata perbedaannya terletak pada masalah ketelitian. Termometer kelvin diakui memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi. Selain itu, ada penemuan berharga kelvin yang diabadikan dalam termometernya. Kelvin menemukan bahwa titik -273,15 derajat celcius adalah suhu terendah yang mungkin terjadi. Pada suhu tersebut seluruh molekul atom tidak dapat bergerak. Pada suhu normal mereka dinamis, jika dipertemukan molekul satu dengan yang lain, dapat dengan mudah terjadi reaksi. Namun pada suhu tersebut ia diam saja. Titik ini kemudian diberi nama nol mutlak atau nol absolut (absolute zero). Kelvin menjadikan titik -273,15 derajat celcius pada titik 0 skala termometernya. Otomatis titik 0 derajat celcius berada pada skala 273,15 derajat kelvin, dan titik 100 derajat celcius ada di titik 373,15 derajat kelvin.
Kenapa termometer harus bermacam-macam? Kenapa tidak satu jenis saja? Ternyata perbedaannya terletak pada masalah ketelitian. Termometer kelvin diakui memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi. Selain itu, ada penemuan berharga kelvin yang diabadikan dalam termometernya. Kelvin menemukan bahwa titik -273,15 derajat celcius adalah suhu terendah yang mungkin terjadi. Pada suhu tersebut seluruh molekul atom tidak dapat bergerak. Pada suhu normal mereka dinamis, jika dipertemukan molekul satu dengan yang lain, dapat dengan mudah terjadi reaksi. Namun pada suhu tersebut ia diam saja. Titik ini kemudian diberi nama nol mutlak atau nol absolut (absolute zero). Kelvin menjadikan titik -273,15 derajat celcius pada titik 0 skala termometernya. Otomatis titik 0 derajat celcius berada pada skala 273,15 derajat kelvin, dan titik 100 derajat celcius ada di titik 373,15 derajat kelvin.
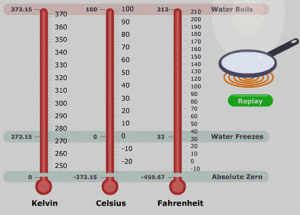
Nah, apa yang dikatakan Kelvin? Kelvin pernah mengucapkan kalimat legendaris yang tertulis di banyak handbook fisika, di sekolah-sekolah kita:
“Anda dikatakan telah memahami sesuatu, hanya bila anda dapat mengukurnya, dan mengekspresikannya dalam angka. Bila tidak berarti pengetahuan anda belum lengkap.”Dalam bahasa yang lain bisa dikatakan, kita dikatakan belum memiliki ilmu tentang sesuatu, sampai kita sudah bisa mengukurnya. Lebih jauh lagi ucapan Kelvin juga bisa ditafsirkan, kalau kita, dan bangsa kita ingin unggul dalam satu bidang, maka kita harus pintar melakukan pengukuran dalam bidang tersebut.
Apa yang diukur? Ya, apa saja.
Segala benda dan materi yang kita lihat di alam semesta ini tak lepas dari ukuran-ukuran. Celcius adalah ukuran untuk mengukur temperatur ruangan. Meter, digunakan untuk mengukur lebar rumah dan luas halaman. Liter (dm3) untuk mengukur volume cairan. Kilogram untuk mengukur berat. Dan jika kita perhatikan, semua memiliki alat ukurnya masing-masing. Untuk mengukur tinggi lemari, digunakan meteran kayu yang bisa diselipkan di pinggang. Namun bagaimana jika yang ingin diukur adalah tinggi gunung? Perlukah kita mengukur tinggi gunung, dengan cara apa mengukurnya? Apa bisa dengan meteran kayu?
Ketinggian gunung perlu diukur. Kita bisa bayangkan, bagaimana jika pesawat yang sedang melintasi batas utara wilayah DIY dan Jateng tidak mengetahui tinggi gunung Merapi secara pasti? Pastinya sangat beresiko. Pesawat bisa menabrak gunung seperti yang terjadi di Gn.Salak beberapa tahun lalu. Sementara ketika berada diatas, sudah tidak mungkin lagi melihat ke bawah. Gunung memiliki ukuran ketinggian, dan konsep cara mengukurnya berbeda dengan cara mengukur tinggi lemari.
Tanpa satuan desibel kita tidak bisa mendengarkan suara dari speaker seperti sekarang. Tanpa satuan volt, ampere, watt, ohm, dan tesla, kita mungkin masih terselimut gelap karena tiadanya listrik yang menyalakan lampu-lampu. Tanpa satuan Hertz, kita tidak bisa menikmati siaran TV dan Radio. Tanpa satuan informasi : byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terrabyte, jelas kita tak akan berada pada era komputer seperti hari ini.
Pertanyaannya, siapakah yang mengukur dan membuat istilah-istilah ukuran tadi? Apakah orang Bantul? Apakah orang Sunda? Apa ia Indonesia? Jelas bukan. Mereka orang-orang yang jauh tinggal di Jepang, Eropa, Amerika, dan negara-negara yang sekarang kita gelari “maju”. Benarlah yang dikatakan Kelvin. Ia yang maju dalam satu bidang, adalah ia yang pandai membuat pengukuran pada bidang itu.
Sebenarnya pengukuran juga bukan melulu dominasi para saintis. Harus diingat bahwa sifat ukuran juga bisa kualitatif, bukan kuantitatif (dengan angka-angka). Ukuran kualitatif bicara banyak-sedikit, baik buruk, keren-cupu, sopan-amoral, dan sebagainya. Jika kita tarik ke bidang seni dan budaya, budaya bangsa mana yang hari ini menjadi trendsetter dan kiblat dunia? Tak lain dan tak bukan adalah bangsa yang pandai menentukan ukuran keren, gaul, dan modis, untuk kemudian diekspor ke bangsa-bangsa lain yang rendah nilai tawarnya.
ISLAM SEBAGAI ALAT UKUR
Sahabat sekalian, semua yang penulis utarakan diatas terkait dengan sains, iptek dan kebudayaan. Dan jika kita bicara tentang Islam, maka Islam juga punya ukuran-ukuran. Ukuran-ukuran inilah yang menjamin bahwa Islam adalah agama yang dibutuhkan manusia akhir zaman. Ukuran ini juga yang menjamin ketentraman dan kebahagiaan manusia. Ukuran tersebut adalah ukuran tentang amal perbuatan kita.
Seluruh perbuatan manusia termasuk status benda, bisa ditimbang dengan timbangan Islam. Kita mengenal hukum yang lima (ahkamul khomsah), “wajib, sunah, mubah, makruh, haram”. Islam bisa mengukur, apa hukumnya makan? Apa hukumnya makan nasi? Apa hukumnya makan nasi milik tetangga? Apa hukumnya makan nasi milik sendiri jam 12 siang di bulan Ramadhan? Pasti bisa diukur. Apa hukumnya mengorek hidung? Apa hukumnya mengorek hidung saat puasa? Apa hukumnya terkorek hidung? Apa hukumnya mengorek hidung sampai berdarah? Apa hukumnya mengorekkan hidung presiden? Hiii, ga usah dibayangin ya, hukumnya ‘njijiki’. :D
Ternyata segala perbuatan secara mendetil dapat diukur dengan Islam. Begitu juga dengan benda. Bedanya, jika hukum perbuatan ada lima, maka hukum benda hanya ada dua, yakni halal, dan haram.
Ukuran-ukuran inilah yang disebut hukum syara’. Inilah ukuran yang menjadi keunggulan umat Islam yang tidak dimiliki bangsa, dan umat lain di seluruh dunia. Bangsa-bangsa lain di dunia, paling banter hanya memiliki ukuran baik dan buruk untuk perbuatan. Masing-masing dari bangsa tadi juga memiliki padanan kata yang berbeda dalam bahasanya. “Baik” dalam Bahasa Indonesia, adalah good, fine, well, nice, dalam Bahasa Inggris. Apik, sae, becik, dalam Bahasa Jawa. Khoir, atau hasan, dalam Bahasa Arabnya. Sedangkan buruk dalam bahasa Indonesia, sepadan dengan bad (Inggris), elek/olo (Jawa), syarr/qobih (Arab). Ukuran dan istilah baik-buruk, dimiliki banyak bangsa, dengan definisinya masing-masing.
Berbeda dengan istilah Islam untuk kata “haram”. Apa bahasa Jawanya “haram”? Haram. Bahasa Inggrisnya, China-nya, Koreanya? Haram juga. Sama dengan kata halal. Tidak kita temukan, kecuali pasti kembali ke istilah asalnya dalam Bahasa Arab, halal.
Selain itu, ukuran hukum syara’ (lima hukum perbuatan + dua hukum benda) juga terbukti unggul dibanding statusisasi (jadi inget siapa ya (: ) baik buruk-nya standar buatan bangsa-bangsa. Jika syara’ mengatakan satu hal itu buruk, maka pasti ia akan buruk selamanya. Jika syara’ mengatakan sesuatu itu baik, niscaya ia baik selamanya. Tidak seperti ukuran-ukuran nisbi yang dibuat manusia. “Esuk dele, sore tempe”, adagium bagi orang yang sering berpindah pendirian, karena sadar, apa yang ia anggap baik pada suatu saat, ternyata buruk pada waktu berikutnya. Hukum syara’ menjamin ketentraman seorang mukmin bahwa, pilihan ia dalam berbuat adalah pilihan yang baik bagi dunianya sekaligus akhiratnya.
Keunggulan inilah yang tidak banyak disadari dan dipahami kaum muslimin. Alih-alih dipandang sebagai keunggulan, hukum syara’ justru dipandang sebagai sesuatu yang mengekang dan memasung kebebasan. Sering kita dengar celetukan,
“kalau lagi bisnis ngga usah bicara halal dan haram deh. Cari yang haram aja susah, apalagi yang haram. Tau gak? Sekarang itu udah ga ada lagi halal-haram, yang ada ‘HALAM’.” (:
“Kalau lagi ngomongin politik, ga usah bawa-bawa agama bro, emangnya Indonesia negara Islam? Ngomong Islam itu di masjid aja kali.”
Orang-orang risih kalau kita bicara dikaitkan dengan Islam. Tidak masalah jika mereka bukan muslim. Nyesek itu kalau kita tahu ia muslim, bahkan pernah mondok atau kuliah di kampus Islam. Gelarnya LC, ustadz, atau kiai haji, tapi bicaranya sekulerisasi. Na’udzubillah min dzalik.
***
Umat Islam jauh dari standar dan ukuran yang harusnya mereka pegang dan emban. Padahal hal inilah yang membuat mereka mundur dan jatuh di neraka krisis ekonomi, tidak berwibawa, terbelakang di segala bidang, dan berpuas dengan title ‘negara berkembang’. Kaum muslimin juga tertindas dan terjajah dimana-mana, di Pattani dan Rohingya, Damaskus hingga Jalur Gaza. Disadari atau tidak, semua ini adalah akibat ulah mereka sendiri yang mengabaikan ukuran-ukuran dalam akidahnya.
Dengan ukuran apa para penguasa kita menentukan, gunung emas di Papua harus dikelola mandiri atau diserahkan hak kelolanya pada PT.Freeport McMoran? Apakah ukuran halal dan haram? Tidak. Mereka mengatakan, bangsa kita belum memiliki teknologi yang cukup, sementara untuk belajar teknologi perlu waktu lama. Daripada kelamaan, kita serahkan saja pada tuan Amerika.
Dengan ukuran apa, sistem ekonomi ribawi hingga hari ini terus kita pertahankan? Apakah ukuran halal dan haram? Ukuran manfaat dan mudharat. Toh namanya aja ‘bunga’, kan bagus, bisa turut melumasi perekonomian. Toh semua negara juga pakai sistem riba.
Dengan ukuran apa, sistem politik demokrasi ujug-ujug dikatakan wajib untuk diterapkan di negeri mayoritas muslim ini? Alih-alih mencari kebenaran, kita telah dididik mencari pembenaran dan pembenaran atas kesalahan memilih sistem yang kita lakukan sejak awal.
Saat ini pemilu tengah berlangsung, dan pakar ekonomi telah membuat hitung-hitungan. Jika Indonesia ingin ekonominya lebih maju dan berkembang, mau tidak mau, subsidi harus terus dikurangi sampai benar-benar tercabut. Naiknya harga dasar listrik, BBM, dan harga-harga barang adalah konsekuensi dari pencabutan subsidi ini. Ini yang terjadi, tatkala rakyat bukan lagi dipandang sebagai gembalaan yang dipelihara urusan-urusannya, sebagaimana Islam memandang mereka. Namun rakyat justru dipandang sebagai konsumen dari perusahaan besar bernama negara.
Ini yang terjadi saat hukum syara’, kita abaikan, kita tinggalkan.
Sahabat yang mulia, radhiyallahu ‘anhu, Umar Ibnul Khattab, pernah berpesan kepada kita:
Sesungguhnya, dulu kita adalah kaum yang terhina. Lalu Allah meninggikan kemuliaan kita dengan Islam. Demi Allah, andai saja kita mencari kemuliaan selain darinya (Islam), pastilah Allah akan kembali menghinakan kita.
Masihkah kita mencari kemuliaan dengan ukuran yang kita buat-buat dengan hawa nafsu sendiri? Atau bahkan ukuran yang ditentukan kaum kuffar di barat yang terbukti gagal mengatur dunia ini? Sesungguhnya kemuliaan dan ketinggian hanya ada pada Islam, maka tidak pantas seorang muslim merasa rendah diri, inferior dengan ukuran yang datang dari Rabbnya, seraya berbangga diri dan mengambil ukuran-ukuran selain darinya.
Allah SWT berfirman:
وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الأعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman.”
(QS. Ali Imran : 139)










